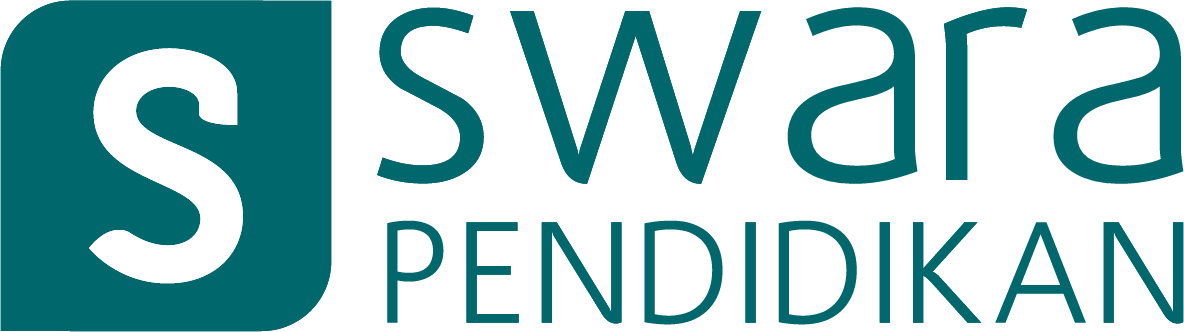Oleh: A. Effendi Kadarisman
Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
Buku “Berbagai Aliran Linguistik Abad XX” ini ditulis agar ahli kita dalam ilmu bahasa tidak dogmatis dan menjadi ilmuwan yang picik, yang menganggap teorinya paling benar (Samsuri 1988: xi).
I cut off my name into two parts: Sam and Suri. Most people would say, “Hi Sam”. A few others would greet me, “Good morning, Mr. Suri” (dari catatan kuliah 1981).
Pada Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) I, yang diselenggarakan di Batu pada bulan November 2009, di awal prosiding yang dibagikan kepada peserta kongres ada rubrik “Wartamerta”, Obituari, yang ditulis oleh Profesor Anton Moeliono. “Masyarakat Linguistik Indonesia dalam waktu yang berdekatan ditinggalkan pakar linguistiknya yang terkemuka” (hlm. xxxi). Keempat pakar itu semuanya wafat pada tahun 2009: Profesor Samsuri, Profesor Asim Gunarwan, Profesor Amran Halim, dan Profesor Soenjono Dardjowidjojo. Mereka layak diberi julukan “pendekar bahasa”, karena “keempat guru besar itu selalu berhati-hati dalam kata dan tulisannya. Ciri bersama lain yang mereka miliki ialah peluang menyelesaikan studi doktornya di Amerika Serikat dan mengabdikan ilmu pengetahuannya demi maslahat kalangan yang luas: pemerintah, rekan setara, mahasiswa, dan anak buah” (ibid.). Belum sampai dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 25 Juli 2011, Profesor Anton Moeliono, yang juga pendekar bahasa, menyusul mereka menghadap Tuhan yang Pengasih.
Kini, menyambut Lustrum Universitas Negeri Malang XII, selayaknya kita mengenang Pak Samsuri (saya merasa lebih akrab menyebut beliau demikian) sebagai salah satu pakar ilmu bahasa di tanah air. Untuk menghemat rujukan, ada baiknya tulisan ini diawali dengan menyebutkan sepuluh karya penting beliau.1 Karya pertama adalah The Phonology of Javanese (1958), tesis master beliau di Universitas Indiana, Bloomington. Tujuh tahun kemudian, disusul oleh karya kedua, An Introduction to Rappang Bugenese Grammar (1965), disertasi beliau di universitas yang sama. Setelah mendapatkan gelar Ph.D, beliau kembali ke Indonesia, ke Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), IKIP Malang. Setahun kemudian, beliau menjabat Dekan FKSS (1966-1969). Berikutnya, beliau memangku jabatan Rektor IKIP Malang (1970-1974). Dalam periode itu, beliau memperoleh gelar guru besar di bidang linguistik, dan menyampaikan pidato pengukuhannya pada tahun 1972. Karya ilmiah ketiga ini berjudul “Memilih Kerangka Acuan Tata-bahasa Bahasa Indonesia”. Kesibukan beliau sebagai pemimpin dan administrator perguruan tinggi menyisakan sedikit waktu untuk meneliti dan menulis. Baru empat tahun kemudian, setelah lengser dari rektorat, beliau menerbitkan Analisis Bahasa: Memahami Bahasa Secara Ilmiah (1978). Karya keempat ini merupakan buku penting bagi para bahasawan dan mahasiswa Jurusan Linguistik di Indonesia. Buku ini membahas tata-bunyi, tata- kata, dan tata-kalimat, dengan latihan yang sangat intensif di bidang fonologi dan morfologi. Tujuh tahun kemudian muncullah Tata Kalimat Bahasa Indonesia (1985) sebagai karya kelima, yang menggunakan kerangka acuan gado-gado dengan aroma transformasi generatif yang kental. Pada “Prawacana” dinyatakan bahwa buku tata- kalimat ini adalah buku pertama, yang akan disusul oleh buku kedua dan ketiga, tata- kata dan tata-bunyi bahasa Indonesia. Tahun 1988 muncullah buku kedua yang dijanjikan, Morfologi dan Pembentukan Kata. Pada tahun itu juga, karya keenam ini disusul karya ketujuh, Berbagai Aliran Linguistik Abad XX (1988). Buku kajian teori ini merupakan hasil studi pustaka yang mendalam, yang dilakukan Pak Samsuri di Universitas Negara Bagian Ohio selama tiga bulan, Juli sampai dengan Oktober 1986. Ketiga karya terakhir berupa artikel: “Referensi dan Inferensi di dalam Wacana” (1990), “Kemampuan Pembicara Bahasa Jawa: Suatu Studi Permulaan” (1993), dan “Pengaruh Bahasa Indonesia pada Pemakaian Unggah-ungguh Bahasa Jawa” (1994).
Sayang sekali, sepuluh karya-tama tersebut tidak bisa saya temukan semuanya, untuk kemudian dirangkum dan diulas secara singkat dan sekaligus digunakan sebagai bahan rujukan bagi tulisan kecil ini. Karena dikejar tenggat (dead line) dan hanya tiga buku plus tiga artikel yang bisa ditemukan, “resensi” ilmu bahasa Pak Samsuri terpaksa bertolak hanya dengan enam karya tersebut. Demi penghematan dan kemudahan, tiga buku yang akan saya ulas dipangkas judulnya menjadi Analisis Bahasa, Tata Kalimat, dan Aliran Linguistik, sedangkan tiga artikel terakhir dipangkas dengan sedikit perubahan menjadi “Studi Wacana”, “Kemampuan Pembicara BJ” dan “Pengaruh BI pada BJ”. Dalam mengutip keenam sumber ini, baik secara langsung maupun tak langsung, saya hanya menyebut tahun penerbitan masing-masing: 1978, 1985, 1988, 1990, 1993, dan 1994. Pada daftar pustaka di akhir tulisan ini, tahun penerbitan Analisis Bahasa dicantumkan (1978 [1985]), yang berarti bahwa buku ini terbit pada tahun 1978, tetapi kopi yang saya gunakan sebagai rujukan adalah cetakan 1985. Jadi, halaman yang saya rujuk adalah versi 1985.
Sebagai begawan linguistik, Pak Samsuri adalah salah satu pilar penyangga kebesaran dan ketenaran IKIP Malang, beliau memasuki masa purnabakti tahun 1990, atau sembilan tahun sebelum IKIP Malang berubah nama menjadi Universitas Negeri Malang (UM). Pada pemikiran linguistik dan pribadi Pak Samsuri, ada empat hal yang menarik untuk dikaji: (1) sikap ilmiah, (2) upaya ikut membakukan bahasa Indonesia, (3) merengkuh linguistik-makro dan menengok kembali bahasa Jawa, dan (3) sisi humanistik dari kehidupan beliau.
SIKAP ILMIAH: KRITIS, KONTEMPORER, DAN PEDULI
Setiap ilmuwan dituntut bersikap kritis. Tanpa sikap ini ia hanyalah sarjana- semu. Sikap ini nampak jelas pada diri Pak Samsuri, yang secara eksplisit menolak dogmatisme (1988: xi), yang mengakibatkan ilmuwan bahasa mengkaji objek penelitiannya dengan kacamata kuda. Sikap kritis, anti-dogma, dan anti-katak- dalam-tempurung ini seirama dengan pandangan Sampson (1980: 10): the greatest danger in scholarship, and perhaps especially in linguistics, is not that the individual may fail to master the thought of a school but that a school may succeed in mastering the thought of the individual (Bahaya terbesar dalam keilmuan, dan mungkin terutama di bidang linguistik, bukanlah kegagalan seorang sarjana dalam menguasai gagasan sebuah aliran linguistik, melainkan keberhasilan sebuah aliran linguistik dalam menguasai atau memerangkap pikiran seorang sarjana.) Kata-kata tajam dari Sampson ini merupakan sindiran terhadap para bahasawan muda, yang di era 1970-an menjadi pengikut fanatik Chomsky dan suka bersikap “sok jagoan”. Sikap sok jagoan para pengagum Chomsky ini juga diungkap oleh Newmeyer (1986: 40), yang prihatin terhadap para mahasiswa Amerika yang ilmunya baru seujung-kuku tetapi sering kehilangan sopan-santun sewaktu berdebat dengan dosen-dosen senior mereka, yang masih setia menganut aliran neo-Bloomfieldian. Jadi, sikap si-katak- berlagak-lembu ini rupanya merata di seluruh dunia.
Pak Samsuri juga kritis terhadap penggunaan kosakata yang “mencemari” bahasa Indonesia, baik yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing (1985: 22). Bila diperlukan untuk mengisi kekosongan konsep dalam bahasa Indonesia, kosakata itu dapat diterima, misalnya masuknya kata-kata menyumbangkan, menangani, sarana, usaha patungan, dan unggul dari bahasa Jawa. Tetapi, jika sudah ada kosakata bahasa Indonesia yang mapan, kosakata dari bahasa daerah tidak diperlukan, seperti belasungkawa untuk berkabung, blak-blakan untuk terus terang, dan tuna-susila untuk pelacur. Tentu saja pendapat beliau ini memicu perdebatan, terutama untuk contoh terakhir. Rupanya eufemisme atau penghalusan makna mendorong munculnya bentuk-bentuk bersaing dengan kosakata yang telah ada: tuna-karya vs. penganggur, tuna-netra vs. buta, tuna-rungu vs. tuli, tuna-wicara vs. bisu, dan banyak ungkapan lain yang menggunakan kata “tuna”. Seandainya ikan “tuna” mengerti bahasa Indonesia, ia pasti menyesal bernama demikian.
Kosakata asing, terutama dari bahasa Inggris, juga mendesakkan diri ke dalam bahasa Indonesia. Jakarta dilanda perasaan rendah diri (1985: 109), sehingga lebih menyukai nama atau istilah bahasa Inggris: Jakarta Convention Hall, Jakarta Fair, Shopping Center Anu. Tiga dasawarsa kemudian kota-kota lain tak mau ketinggalan, dan muncullah Cirebon Town Square (Citos), Surabaya Town Square (Sutos), dan Malang Town Square (Matos). Mungkin hanya Jombang yang tidak bersemangat menggunakan nama serupa, karena Jombang Town Square akan disingkat “Jotos”. Di sebuah stasiun TV juga banyak acara bertema bahasa Inggris: Headline News, Prime Time, Today’s Dialogue, Wide Shot. Apakah ini juga gejala rasa rendah diri, atau karena keinginan go international? Sejumlah nama produk untuk kesehatan juga demikian: fatigone (fatigue gone = rasa-lelah punah), gazero (gas zero = udara- busuk nol), dan pain kila (ucapan logat British dari pain killer = penghilang nyeri). Nama-nama dengan bahasa Inggris ini semua terkait dengan pemasaran, dan nama barang atau jasa yang dijual memang harus menarik minat pembeli. Riverside Estate, kata almarhum Pak Soenjono dalam sebuah rubrik “Bahasa” di Tempo, tentu jauh lebih memikat daripada Perumahan Pinggir Kali. Ketika kepentingan bisnis mendesakkan diri, apakah kemurnian bahasa Indonesia harus mengalah dan menyisih? Ini pertanyaan yang menarik dan perlu dijawab oleh para ahli sosiolinguistik.
Nama-nama gedung dan penghargaan pemerintah dengan bahasa Sansekerta juga dikritik oleh Pak Samsuri. Orang Belanda suka memungut kata-kata dari bahasa Latin atau Yunani Kuno, dan orang Indonesia meniru mereka dengan memungut kata-kata dari bahasa Sansekerta dan Jawa Kuno. Ini mencerminkan jiwa kerdil dan juga sikap merendahkan bahasa nasional (1985: 22 dan 109-10). Ironisnya, dari nama-nama bangunan yang terdengar anggun seperti Bina Graha (Rumah Pembina) dan Manggala Wana Bhakti (Bakti-setia Pasukan Penjaga Hutan), para mantan penghuninya kemudian diragukan kejujurannya. Benarkah mereka raja dibya lan satria tama (raja sakti dan kesatria utama), atau narendra myang prawira cidra (raja dan perwira pendusta)? Nama mentereng juga digunakan untuk penghargaan provinsi, kotamadya, atau kabupaten terbaik: Parasamya Purnakarya Nugrana (Hadiah untuk Karya-terbaik yang Dilaksanakan Bersama-sama). Benarkah prestasi itu diraih melalui kerja-sama yang jujur? Sering beredar isu bahwa penghargaan itu diterima lewat tawar-menawar di bawah meja. Ada pengalaman menarik. Jika pulang ke Kediri (selatan), saya selalu lewat Blitar. Di beberapa tempat terpampang semboyan: Hurup Hambangun Praja. Apa arti ungkapan ini? Atas penjelasan Profesor A. Syukur Ghazali, saya baru tahu maknanya: Bersemangat Membangun Wilayah. Pertanyaannya kemudian: semboyan ini mengajak rakyat untuk membangun wilayah, atau pamer bahwa pemerintah yang hebat adalah penguasa yang berbicara kepada rakyatnya dengan bahasa yang tidak mereka mengerti?
Selain kritis, Pak Samsuri juga seorang bahasawan kontemporer. Semasa hidupnya, beliau selalu mengikuti perkembangan teori linguistik mutakhir. Ini sudah nampak sewaktu beliau menyelesaikan program doktor di Universitias Indiana. Disertasi beliau, An Introduction to Rappang Bugenese Grammar, selesai ditulis pada tahun 1965. Disertasi ini menggunakan “teori transformasi” sebagai acuan teoritis (1978: 80), padahal teori ini baru dituangkan secara tuntas oleh Chomsky dalam Aspects of the Theory of Syntax, yang terbit tahun 1965 juga. Ini menunjukkan betapa up-to-date pemikiran linguistik Pak Samsuri pada awal karier ilmiahnya. Setelah beliau kembali ke Indonesia, dan menekuni profesi linguistik dengan mengajar dan meneliti, beliau masih sering melakukan surat-menyurat langsung dengan Chomsky, untuk minta penjelasan tentang hal-hal yang pelik dalam linguistik generatif (komunikasi lisan dengan Profesor Moh. Adnan Latief, September 2014). Sikap kontemporer dan up-to-date beliau juga terbaca pada Analisis Bahasa, yang bab terakhirnya, Bab 25, berjudul “Lahirnya Semantik Generatif”. Buku ini terbit tahun 1978, dan Semantik Generatif adalah aliran radikal yang berumur pendek: muncul di akhir 1960-an dan punah di akhir 1970-an. Artinya, sewaktu Analisis Bahasa itu terbit, Semantik Generatif, menurut The Linguistics Wars karya Harris (1995), sedang melakukan “perang” habis-habisan melawan Gramatika Generatif, sebelum akhirnya tumbang di ujung dasawarsa itu. Pada tahun terakhir pengabdiannya di IKIP Malang, beliau tetap aktif mengikuti perkembangan linguistik mutakhir, dan hasilnya adalah “Studi Wacana” yang terbit tahun 1990.
Sikap terpuji ketiga adalah sikap peduli. Pak Samsuri sangat peduli terhadap pembaca bukunya dan bahasawan lain, terhadap bahasa Indonesia, terhadap hubungan bahasa dengan sastra, politik, dan ilmu pengetahuan, dan juga terhadap pengajaran bahasa. Orang besar adalah orang yang memiliki kepedulian yang besar. Pembahasan berikut akan mencermati kepedulian besar ini, dan mengulas cakupannya dengan singkat satu-persatu.
Kepedulian Pak Samsuri terhadap pembaca bukunya nampak pada bahasa yang digunakan: jernih dan runtut, sehingga mudah dibaca dan dipahami. Untuk memudahkan pemahaman konsep de Saussure tentang kata-kata sebagai “arbitrary signs”, misalnya, beliau menjelaskannya dalam Analisis Bahasa sepanjang tiga halaman (1978: 10-14), dengan memberikan banyak contoh dan paparan yang gamblang. Maka peminat linguistik pemula akan mudah memahami konsep tersebut. Beliau juga peduli terhadap para bahasawan lain, dengan mendorong mereka untuk terus berkarya sesuai dengan teori yang dikuasai dan dianutnya, sehingga berbagai teori tentang bahasa Indonesia akan muncul sebagai bunga- rampai yang indah dan saling melengkapi (1985: ix-x).
Terhadap bahasa Indonesia, beliau menunjukkan rasa cinta dan kepedulian yang besar. Pada tahun 1960, lima tahun sebelum meraih gelar Ph.D. di bidang linguistik, beliau telah mengemukakan konsep pembaharuan ejaan bahasa Indonesia (Badudu 1984: 44-46). Gagasan ini menjadi salah satu cikal-bakal bagi munculnya Ejaan yang Disempurnakan (EYD), yang mulai berlaku tahun 1972. Tata Kalimat beliau terbit tahun 1985, mendahului Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TBBI), yang terbit pertama kali tahun 1988, bersama Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)—dalam rangka Kongres Bahasa Indonesia V. Beliau juga anggota tim penyusun TBBI. Ini adalah langkah besar bagi kemajuan bahasa Indonesia, lewat upaya pembakuan yang secara resmi diprakarsai oleh pemerintah Indonesia, lewat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Upaya ini terkait langsung dengan politik bahasa—catatan tambahan yang penting dicantumkan di sini. Dibandingkan dengan bahasa nasional atau bahasa resmi di banyak negara (misalnya Malaysia, Filipina, India, dan negara-negara kecil di benua Afrika), bahasa Indonesia memiliki posisi politis yang sangat beruntung (1978: 27-31). Di seluruh penjuru tanah air, tidak ada kelompok masyarakat yang menolak, memusuhi, atau membenci bahasa Indonesia. Tambahan lagi, kosakata bahasa Indonesia telah tumbuh begitu pesat. Selama paroh-kedua abad kedua puluh, melalui rekayasa bahasa, telah terjadi “ledakan jumlah kosakata” yang begitu besar dalam konteks modernisasi, politik pembangunan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Samuel 2005 [2008]: 250-51, 392). Hasilnya, bahasa Indonesia kini dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang memadai dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Terkait dengan perkembangan bahasa Melayu di Asia Tenggara (meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunai Darussalam), optimisme juga terasa begitu tinggi, sehingga Profesor James Collins (1998 [2011]), pakar dialektologi Melayu, meramalkan bahwa di masa depan bahasa Melayu—dengan sekitar 300 juta penutur di tahun 2020—layak menjadi salah satu bahasa dunia.
Kembali ke akhir tahun 1970-an, Pak Samsuri prihatin terhadap keberaksaraan dalam bahasa Indonesia, terutama di dunia akademik. Walaupun sebagai alat komunikasi lisan bahasa Indonesia telah begitu mapan, penggunaannya sebagai bahasa ilmu pengetahuan masih sangat compang-camping. Ini terlihat dari sangat sedikitnya (pada waktu itu) buku-buku ilmu pengetahuan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. “Jika Pemerintah tidak lekas-lekas mengambil langkah-langkah untuk memperbanyak buku-buku di dalam bahasa Indonesia, kami takut … kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia akan terhambat sekali, karena kenyataan bahwa sarjana- sarjana kita pada umumnya sukar sekali mengerti buku-buku di dalam bahasa asing” (1978: 31).
Dalam membahas hubungan antara bahasa dan sastra, pandangan Pak Samsuri (1978: 24-26) mirip dengan gagasan Sapir (1921: 221-31). Setiap bahasa bersifat relatif, masing-masing memiliki wujud bunyi, struktur kata, dan struktur kalimat yang khas. “Since every language has its distinctive peculiarities, the innate formal limitations—and possibilities—of one literature are not quite the same as those of another” (Karena setiap bahasa memiliki sifat atau fitur yang khas, keterbatasan dan juga kemungkinan bentuk intrinsik dari setiap sastra tidak pernah sama dengan sastra yang lain, hlm. 222.) Misalnya, sastra Jawa, sastra Indonesia, sastra Arab, dan sastra Inggris berbeda satu sama lain, karena kekhasan struktur dari masing-masing bahasa yang menjadi medium setiap sastra tersebut. Ini berakibat pada sulitnya penerjemahan karya sastra, terutama puisi. “Poetry by definition is untranslatable,” kata Jakobson (1959 [1992]: 151). Pak Samsuri, mengutip Groce, juga menyetujui pendapat Jakobson ini, “suatu [karya] sastra tidak mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain”, meskipun tetap ada perkecualian. Bahkan tidak sedikit karya sastra yang berhasil diterjemahkan dengan baik dari satu bahasa ke bahasa lain. Contoh yang diberikan oleh Pak Samsuri adalah puisi “Nisan”, karya Chairil Anwar, yang diterjemahkan dengan cantik oleh Burton Raffel ke dalam bahasa Inggris (1978: 25). Keunikan atau keanehan wujud bahasa pada karya sastra, menurut tinjauan linguistik, pada akhirnya berpulang pada pertanyaan Jakobson (1960 [1987]), “What makes a verbal message a work of art?” (Apa yang menjadikan pesan verbal sebuah karya sastra?) Jawaban Jakobson, sebagai penyair-bahasawan, lebih bersifat struktural daripada substansial. Dia tidak mengupas “isi” karya sastra, melainkan memaparkan “bentuk”nya. Untuk itu, ia mengajukan “fungsi puitik”: selalu ada bentuk khas yang ditonjolkan oleh setiap bahasa demi mencapai tujuan estetik yang dimaksudkan.
Bagaimana hubungan antara linguistik dan pengajaran bahasa? Sebagai bahasawan, Pak Samsuri (1978: 40-44) percaya bahwa metode-dan-praktik pengajaran bahasa ditentukan atau paling tidak dipengaruhi oleh perkembangan linguistik. Meskipun secara formal, linguistik sinkronik baru muncul di awal abad kedua-puluh, “ilmu bahasa” pada wujudnya yang masih tradisional telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Pengajaran bahasa Sansekerta di India sebelum tarikh masehi dipengaruhi oleh tata-bahasa karya Panini. Pengajaran bahasa Yunani Kuno tidak lepas dari pandangan Plato dan Aristoteles tentang hakikat dan arti bahasa. Di zaman abad pertengahan, pengajaran bahasa di negara-negara Eropa difokuskan pada pengajaran bahasa Greko-Latin sebagai bahasa ilmu pengetahuan, mengikuti semangat “Pencerahan”.
Bagaimana pula pengajaran bahasa Indonesia di Indonesia? Pertanyaan yang diajukan Pak Samsuri: “Apakah tujuan pengajaran bahasa nasional itu? Apakah tujuannya mengetahui TENTANG bahasa itu, ataukah tujuannya mempertinggi kemahiran murid-murid dalam MEMEPERGUNAKAN bahasa itu?” (1978: 41, huruf besar pada teks asli). Secara implisit, pertanyaan ini merupakan kritik terhadap praktik pengajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah, yang lebih mengutamakan pengetahuan tentang bahasa daripada keterampilan berbahasa. Padahal yang kedua inilah yang lebih penting, karena ia langsung terkait dengan kegunaan praktis. Lewat pengajaran bahasa Indonesia dengan tujuan-dan-praktik yang benar, siswa akan mampu “menyusun kalimat yang baik, terang dan jelas”. Mereka juga mampu “mengemukakan buah pikiran dengan kalimat-kalimat yang pendek, tegas, dan jelas, dan tidak membingungkan”. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan mampu menyampaikan pidato singkat, jelas, dan santun pada acara- acara perpisahan, ulang tahun, perkawinan, dan sebagainya. Mereka juga mampu menggunakan bahasa tulis dengan efektif: dapat menulis surat atau menyusun laporan dengan logika yang lurus dan bahasa yang jernih (1978: 42). Singkatnya, pengajaran bahasa yang berhasil adalah pengajaran yang pada akhirnya melahirkan manusia yang beradab dan berbudaya melalui tindak-tutur dan bahasanya.
MEMBAKUKAN, BUKAN MEMBEKUKAN BAHASAINDONESIA
Ungkapan cantik “membakukan, bukan membekukan bahasa” ini saya pinjam dari Dr. Sudaryanto (1991: 1-2), pakar linguistik dan dosen Pascasarjana Universitas Widya Dharma, Klaten, dan penyunting utama buku Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa. Seperti sikap Pak Sudaryanto terhadap bahasa Jawa, Pak Samsuri juga percaya bahwa upaya membakukan bahasa Indonesia bukan berarti membekukannya. Bahasa adalah fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang secara dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat penuturnya. Dinamika bahasa Indonesia nampak jelas pada dua hal: bahasa sebagai ungkap-verbal kebudayaan dan bahasa sebagai wahana pengembangan ilmu dan teknologi (1985: 5-29).
Bahasa Indonesia dan kebudayaan Indonesia merupakan produk abad kedua puluh, dan keduanya tumbuh secara perlahan. Ketika para pendiri bangsa “bersumpah” pada 1928 bahwa mereka “menjoenjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia”, yang ada waktu itu baru gagasan besar, bukan “bahasa nasional” yang siap-pakai (Foulcher 2000: 378-81). Bahasa Melayu yang dipilih dan dinamakan “bahasa Indonesia” saat itu masih harus dibina, dikembangkan seluruh potensinya untuk menjadi bahasa nasional. Begitu pula kebudayaan Indonesia. Ia masih berupa embrio di zaman kolonial Belanda dan Jepang, dan baru muncul secara penuh bersama proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Ketika Indonesia merdeka, identitas nasional diperlukan. Maka kebudayaan yang mencakup aspek kehidupan spiritual dan material di seluruh tanah air adalah kebudayaan Indonesia, dan ungkap-verbal kebudayaan ini adalah bahasa Indonesia. Di antara ratusan bahasa daerah dan puluhan bahasa Indonesia logat yang digunakan sebagai alat komunikasi intra-etnis di seluruh penjuru nusantara (1985: 24-27), diperlukan bahasa Indonesia baku sebagai alat komunikasi antar-etnis—bahasa yang bisa digunakan dan dipahami oleh seluruh warga bangsa Indonesia.
Potret kebahasaan kita dapat disebut diglosia: bahasa Indonesia hidup berdampingan dengan bahasa daerah setempat di semua wilayah di tanah air. Bahasa daerah lazim digunakan sebagai alat komunikasi antar-anggota keluarga dan intra–etnis, dan sebagai bahasa ritual dan upacara adat. Sejumlah bahasa daerah memiliki sastra-tinggi, yang telah berumur ratusan tahun dan menjadi kebanggaan lokal. Sastra-tinggi ini bukan hanya berupa sastra-tulis, melainkan juga memiliki watak kelisanan yang kental. Maka di berbagai daerah—seperti di Aceh, Padang, Sunda, Jawa, Bali, dan Makassar, misalnya—sastra-tinggi itu juga memberi inspirasi dan sekaligus tampil sebagai sastra-lisan (verbal art) atau sastra-pentas (poetic performance). Dengan kata lain, bahasa dan sastra daerah juga berfungsi memelihara kesenian dan kebudayaan daerah. Sebaliknya, bahasa Indonesia diperlukan sebagai bahasa administrasi pemerintahan dan bahasa pengantar di dunia pendidikan. Dengan sifat alaminya yang terbuka, demokratis, sederhana, dan mudah dipelajari (1985: 14), bahasa Indonesia layak dikembangkan menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara bahasa daerah lebih bersifat statis-emotif, bahasa Indonesia bisa digali potensinya dan diarahkan menjadi wahana kebudayaan yang lebih rasional, kreatif, dan produktif. Ini adalah ciri utama kehidupan modern. Hanya dengan memenuhi persyaratan ini, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa abad industri dan pasca-industri (1985: 11-12).
Maka buku Tata Kalimat ditulis demi membantu terwujudnya bahasa Indonesia baku, sebagai alat komunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia dan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat objektif dan universal. Rancang bangun buku ini, yang didukung oleh Analisis Bahasa dan Aliran Linguistik, menunjukkan kepakaran Pak Samsuri di bidang ilmu bahasa, dalam dua hal: (a) dalam pemilahan dan pemilihan ancangan teoritis, dan (b) dalam memaparkan struktur bahasa Indonesia sebagaimana digunakan oleh penuturnya.
Memilah dan Memilih Ancangan Teoritis
Pada “Prawacana” untuk Tata Kalimat, seperti telah disinggung di depan, Pak Samsuri menyatakan bahwa ini adalah buku pertama dari “tiga serangkai”, yang akan segera diikuti oleh buku kedua dan ketiga, yaitu Tata Kata dan Tata Bunyi (1985: ix, 42). Untuk rencana besar memaparkan dan menjelaskan Tata Bahasa Indonesia, diperlukan kerangka teoritis. Teori mana yang digunakan?
Landasan teoritis merupakan pijakan penting bagi bahasawan untuk menata kerangka berpikir, mendapatkan kedalaman analisis, dan mengarahkan hasilnya agar memiliki kegunaan teoritis dan praktis yang jelas. Ketiga buku yang digunakan sebagai rujukan utama tulisan ini menunjukkan pentingnya memahami teori bahasa. Sub-bab “Sejarah Singkat Ilmu Bahasa” dalam Analisis Bahasa (1978: 71-84) dan “Pendekatan Analisis Bahasa” dalam Tata Kalimat (1985: 29-42) meringkas dan menyarikan berbagai teori linguistik yang terkenal. Kedua sub-bab ini kemudian dikembangkan secara penuh menjadi sebuah buku Berbagai Aliran Linguistik Abad XX (1988), yang dalam tulisan ini dipangkas menjadi Aliran Linguistik. Buku ini bertolak dengan menengok kembali studi bahasa selama abad kesembilan-belas, dan kemudian memasuki abad kedua-puluh dengan memaparkan 9 aliran (schools) yang sangat berpengaruh: (1) Aliran Swiss, (2) Aliran Praha, (3) Ilmu Bahasa Fungsional, (4) Aliran Kopenhagen, (5) Aliran Strukturalisme di Amerika, (6) Aliran London, (7) Strukturalisme Amerika, (8) Tatabahasa Generatif Transformasi, dan (9) Perkembangan Ilmu Bahasa sesudah Semantik Generatif. Butir (5) dan (7) nampak mirip, namun isinya berbeda. Butir (5) membahas teori linguistik Franz Boas dan Edward Sapir, sedangkan butir (7) mengupas teori bahasa pasca-Bloomfield dan teori tagmemik Kenneth Pike.
Penjelajahan yang intens terhadap sembilan teori linguistik tersebut membuat Pak Samsuri memiliki pemahaman yang mendalam, pandangan yang terbuka, dan sikap yang toleran terhadap setiap teori yang ada. Untuk menganalisis kalimat, kata, dan bunyi dalam bahasa Indonesia, teori mana yang paling sesuai? Untuk menjawab pertanyaan ini, beliau mengajukan tiga kriteria: kesederhanaan, kehematan, dan ketuntasan analisis dan pemerian merupakan ukuran untuk menilai setiap teori yang ada (1978: 264-67). Berdasarkan tiga kriteria ini, ternyata tidak ada sebuah teori-utuh yang langsung bisa digunakan. Karena itu, beliau “meramu sendiri” sebuah ancangan teoritis (1985: 38-42). Untuk menganalisis bunyi bahasa Indonesia, beliau memadukan teori Praha dan teori pasca-Bloomfield. Kedua teori ini saling mengisi, karena yang pertama terlalu njelimet dalam tata-bunyi, dan yang kedua terlalu global. Perpaduan yang tepat antara keduanya akan menghasilkan pendekatan yang sesuai. Untuk tata-kata, teori pasca-Bloomfield telah memadai. Ini mengingatkan kita bahwa era keemasan aliran Bloomfieldian memang disebut sebagai “the decades of phoneme and morpheme” (Harris 1995: 31), atau dasawarsa fonem dan morfem. Namun, untuk tata-kalimat, teori pasca-Bloomfield tidak bisa diandalkan. Teori ini terlalu dangkal untuk dapat menjelaskan bagaimana kalimat dasar bisa diderivasi menjadi beraneka-ragam kalimat turunan. Untuk itu, yang paling sesuai adalah teori transformasi generatif. Namun, Pak Samsuri juga tidak mengadopsi teori ini seutuhnya, beliau menggunakan teori ini dengan sangat hati-hati—seperti akan dijelaskan kemudian.
Jadi, pendekatan analisis yang digunakan oleh Pak Samsuri adalah “pendekatan eklektik”, atau pendekatan gado-gado. Memang ada dua jenis gado-gado: gado-gado jalan-lurus (enlightened eclecticism) dan gado-gado jalan-sesat (misguided eclecticism). Yang pertama mengambil berbagai unsur dari beberapa teori yang benar-benar dipahami, kemudian diramu menjadi pendekatan baru yang memadai dan hasil analisisnya akan memuaskan. Yang kedua merupakan sikap dan tindakan coba-coba, siapa tahu nanti akan ada hasilnya (Hammerly 1982: 24-25). Ketika Pak Samsuri meramu sendiri pendekatan analisisnya, tentu saja beliau memilih pendekatan eklektik jalan-lurus.
Sifat Alami Kalimat Bahasa Indonesia
Setiap bahasa memiliki sifat khas masing-masing, dan ini nampak jelas pada strukturnya. Kalimat bahasa Indonesia memiliki struktur yang khas, dan analisis bahasa yang benar harus mampu menampilkan sifat alami ini. Inilah yang telah dilakukan Pak Samsuri dalam Tata Kalimat. Meskipun beliau menggunakan teori transformasi generatif, beliau tidak “memaksa” kalimat bahasa Indonesia untuk mematuhi teori ini. Meminjam istilah Comrie (1989: 1-5), pendekatan Tata Kalimat lebih bersifat data-driven daripada theory-driven, atau lebih mengutamakan “apa kata data” daripada “apa kata teori”. Maka yang beliau lakukan bukan adopsi, melainkan adaptasi terhadap teori sintaksis Chomsky (1965). Ada dua modifikasi penting yang beliau lakukan: (i) data introspektif digabung dengan data lapangan, dan (ii) struktur kalimat bahasa Indonesia dipaparkan secara objektif sesuai dengan watak aslinya.
Data Introspektif dan Data Lapangan
Dalam tradisi Chomskyan, data yang dianalisis untuk menguji keabsahan kaidah tata-kalimat cukup diperoleh dari data lingual yang ada dalam diri peneliti, yang disebut “data instrospektif”. Mari kita simak perangkat contoh yang diberikan dalam Tata Kalimat (1985: 64).
(1) a. Anak itu / makan kacang
- Anak itu / makan kacang / dengan lahapnya
- *Anak itu / dengan lahapnya
Sebagai penutur bahasa Indonesia, kita bisa “merasakan” bahwa (1.a) dan (1.b) adalah kalimat yang “baik”, sedangkan (1.c) kalimat yang “janggal”. Dalam sintaksis generatif, “merasakan” berarti ‘menentukan status gramatikal atau tak- gramatikal’, “baik” berarti ‘gramatikal’, dan “janggal” berarti ‘tak-gramatikal’. Setiap penutur bahasa Indonesia memiliki pengetahuan intuitif seperti ini, yang istilah resminya adalah kompetensi bahasa. Dan tujuan linguistik generatif adalah memaparkan dan menjelaskan hakikat kompetensi bahasa. Untuk ini, cukuplah data lingual diperoleh dari diri peneliti sendiri. Maka, linguistik generatif terkadang diejek sebagai “armchair linguistics”, yang terjemahan bebasnya “linguistik kursi goyang”. Data cukup diperoleh dari kepala sendiri, sambil duduk bergoyang, peneliti tidak perlu repot mengumpulkan data lapangan.
Namun, Pak Samsuri melakukan lebih dari itu, beliau menggabungkan data instrospektif dan data lapangan. Ini tidak main-main. Data lapangan beliau kumpulkan dari 16 kota atau “pusat kebudayaan” di tanah air: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Ujung Pandang (sekarang Makassar), dan Manado. Data lapangan berupa data lisan dan data tulis. Data lisan diperoleh melalui rekaman. Di setiap kota dilakukan rekaman selama 9 jam terhadap percakapan dua informan (mahasiswa, dosen, asisten peneliti) atau lebih. Ada dua macam percakapan: intra-etnis menggunakan bahasa Indonesia logat, dan antar-etnis menggunakan bahasa Indonesia baku. Total rekaman lebih-kurang 150 jam, dan secara selektif ditranskripsikan. Sedangkan data tulis dikumpulkan dari berbagai buku dan karangan, fiksi dan non-fiksi, yang ada di setiap kota sejak tahun 1940-an sampai dengan awal tahun 1980-an. Dari setiap karya tulis dipilih secara acak 200 kalimat. Data tulis yang terkumpul lebih-kurang 5000 kalimat.
Dalam Tata Kalimat, data introspektif dan data lapangan ditampilkan sesuai dengan langkah-langkah analisis, untuk menunjukkan berpuluh tipe struktur frasa dan beratus tipe struktur kalimat. Penggunaan data lapangan merupakan bagian utama dari tradisi Bloomfieldian, dan data introspektif (pada waktu itu) merupakan tradisi baru dalam aliran Chomskyan. Gabungan keduanya dapat dipandang sebagai upaya memaparkan de langue (bahasa) dalam paradigma Saussurean. Di sini pendekatan eklektik Pak Samsuri nampak semakin jelas: beliau menggabungkan unsur-unsur dari teori Chomsky, Bloomfield, dan de Saussure.
Struktur Kalimat Bahasa Indonesia
Ada dua watak khas pada struktur kalimat bahasa Indonesia: kelenturan urutan kata atau flexibility of word order, dan predikat yang tidak selalu berupa frasa verba. Kelenturan urutan kata ditunjukkan dalam Tata Kalimat (1985: 64-66), dengan mengulangi kalimat (1.b) sebagai “kalimat dasar” (kernel sentence) bersama 5 kalimat turunannya: (1.b) – (1.f).
- Anak itu / makan kacang / dengan lahapnya
- Anak itu / dengan lahapnya / makan kacang
- Makan kacang / anak itu / dengan lahapnya
- Makan kacang / dengan lahapnya / anak itu
- Dengan lahapnya / anak itu / makan kacang
- Dengan lahapnya / makan kacang / anak itu
Kelenturan urutan kata dalam bahasa Indonesia ini bukan hal baru, dan juga bukan pertama kali ditunjukkan oleh Pak Samsuri. Hal ini telah dibahas dalam buku sintaksis yang jauh lebih tua, Kaidah Bahasa Indonesia I karya Slametmuljana (1957: 17-23). Yang baru dalam Tata Kalimat ialah pendekatan yang digunakan dan pemaparan yang diberikan. Pak Samsuri bukan hanya menunjukkan adanya kelenturan urutan kata itu, melainkan juga menjelaskan bagaimana kalimat dasar itu berubah menjadi berbagai kalimat turunan melalui kaidah transformasi.
Tabel 1. Kaidah Transformasi: dari Kalimat Dasar ke Kalimat Turunan
| Kalimat Dasar | Kalimat Turunan |
| (2.a) FN + FV + FAdv à | (2.b) FN + FAdv + FV
(2.c) FV + FN + Fadv (2.d) FV + FAdv + FN (2.e) FAdv + FN + FV (2.f) FAdv + FV + FN |
Kalimat dasar (2.a) terdiri atas 3 komponen: FN (frasa nomina anak itu), FV (frasa verba makan kacang), dan FAdv (frasa adverbia dengan lahapnya). Perubahan urutan kata dari (2.a) ke (2.b) – (2.f) ditunjukkan melalui penggunaan kaidah transformasi pada Tabel 1. Menurut teori probabilitas, jika ada 3 komponen, maka kemungkinan urutannya ada 6, yang diperoleh dari 3 X (3-1). Pada butir (2), enam kalimat dengan urutan yang berbeda itu semuanya gramatikal. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki kelenturan urutan kata yang sangat tinggi. (Dalam bahasa Inggris, hanya kalimat seperti (2.a) yang gramatikal, The boy is eating peanuts greedily, urutan kata seperti pada lima kalimat lainnya tak- gramatikal.)
Kaidah transformasi tersebut bukan hanya menunjukkan bagaimana kalimat dasar berubah menjadi kalimat turunan, melainkan juga menyajikan secara persis. Berapa jumlahnya dan bagaimana urutan kata masing-masing. Presisi yang tinggi ini bisa dicapai berkat penggunaan formula X Y, yang disebut re–write rule dan bersifat matematis.Menurut Lyons (1978: 59), di sinilah kehebatan Chomksy. Teori linguistiknya sangat mentalistik, karena bertujuan menjelaskan hakikat kompetensi bahasa yang ada dalam pikiran penuturnya. Namun, ia mampu menjabarkan kompetensi tersebut dengan jelas dan tuntas berkat rumus matematis yang diciptakannya.
Selanjutnya, mari kita cermati predikat kalimat dalam bahasa Indonesia. Setelah beredar di kalangan akademisi dan masyarakat luas hampir seperempat abad, buku Tata Kalimat mendapatkan pujian dari Pak Anton Moeliono (2009: xxxi).
Buku sintaksis ini membawa angin segar dalam wawasan tata kalimat kita. Berbeda dengan teori yang dianut pakar bahasa Eropa dan Amerika, yang menyatakan predikat kalimat selalu verba atau salah satu kopula, Samsuri berpendirian bahwa predikat dalam kalimat Indonesia dapat berwujud frasa verba, adjektiva, nomina, numeralia, dan proposisi. Contohnya, Korupsi merajalela (V), Restoran itu istimewa (A), Aku warga kota (N), Tanah Ali tiga hektare (Num), Cerita itu tentang Dewa (P).
“Angin segar” yang melegakan itu berhembus berkat kreativitas Pak Samsuri, yang berpendapat bahwa teori sintaksis generatif perlu disesuaikan dengan watak bahasa Indonesia. Menurut versi aslinya, hanya ada satu formula kalimat: SàNP + VP (Chomsky 1957: 26-27), formula ini dibaca every sentence consists of an NP subject and a VP predicate. Formula ini sepenuhnya benar untuk kalimat bahasa Inggris. Setiap subjek adalah frasa nomina, dan setiap predikat adalah frasa verba, baik verba utama (misalnya, Harry left) maupun kopula (misalnya, Harry is a lawyer). Untunglah Pak Samsuri mengadaptasi formula ini, dan mengubahnya sesuai dengan sifat alami struktur kalimat bahasa Indonesia. Formula kalimat (K) dengan lima jenis predikat berbeda, seperti yang telah disebutkan Pak Anton di depan, ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Struktur Kalimat Bahasa Indonesia
| No. | Formula Kalimat | Contoh | |
| 1 | K ->> | FN + FN | Anak itu murid SMP |
| 2 | FN + FV | Perempuan itu membeli sepatu | |
| 3 | FN + FA | Orang itu malas sekali | |
| 4 | FN + FNum | Pegawai kantor itu hampir tigapuluh orang | |
| 5 | FN + FP | Anak kami di Bandung | |
Hanya formula (2), KàFN + FV (Perempuan itu membeli sepatu), yang sepadan dengan SàNP + VP. Keempat formula lainnya merupakan formula baru, yang diperlukan untuk kalimat dengan predikat non-verba. Mungkin timbul pertanyaan: sesungguhnya, bukankah terdapat kopula adalah yang menghubungkan subjek FN dengan predikat non-verba? Mari kita lakukan uji-sintaktik untuk menjawab pertanyaan ini.
- Anak itu adalah murid SMP
- *Orang itu adalah malas sekali
- *Pegawai kantor itu adalah hampir seratus orang
- *Anak kami adalah di Bandung
Hasil uji-sintaktik menunjukkan bahwa kalimat (3.a) saja yang berterima. Dari segi struktur maupun makna, hadirnya adalah merupakan pemborosan. Tanpa kopula, makna kalimat ini sudah jelas. Sebaliknya, kalimat (3.b), (3.c), dan (3.d) tidak dapat disisipi oleh adalah. Artinya, hadirnya kopula ditolak oleh ketiga kalimat ini. Jadi, watak dasar predikat kalimat bahasa Indonesia terbagi menjadi dua: verba dan non- verba. Predikat non-verba meliputi FN, FA, FNum, dan FP.
Namun, perlu dicatat bahwa kalimat berpredikat verba merupakan tipe paling dominan. Tata Kalimat membahas kalimat dasar dengan struktur FN + FV lebih dari 40 halaman, sedangkan keempat tipe lainnya dibicarakan kurang dari 10 halaman. Nampaknya istilah kata kerja sebagai padanan verba benar-benar membuat sebagian besar kalimat “bekerja” lebih keras. Dengan kata lain, formula S NP VP adalah rumus mutlak dalam bahasa Inggris, tetapi hanya merupakan rumus dominan dalam bahasa Indonesia.
Karena acuan utama Tata Kalimat adalah teori generatif, pembahasan transformasi (perubahan kalimat dari struktur batin ke struktur lahir) menyita lebih dari separoh buku, atau lebih dari 200 halaman. Ini meliputi transformasi yang menghasilkan kalimat turunan tunggal, kalimat sematan, kalimat rapatan, transformasi fokus, dan transformasi khusus. Transformasi kalimat berita menjadi kalimat tanya telah dibahas pada beberapa bagian buku ini (1985: 252-53, 286-89, 447-50). Namun, ada yang belum dibahas secara tuntas, yaitu kalimat tanya yang menggeser kata tanya apa dan siapa dari posisi objek ke awal kalimat.
- Ia mengirimkan paket itu kemarin.
- Apa yang ia kirimkan j kemarin?
- Mereka menemui ketua panitia di ruang sidang.
- Siapa yang mereka temui j di ruang sidang?
Dalam sintaksis generatif, istilah j (jejak) merupakan padanan dari t (trace) dalam bahasa Inggris, yang melambangkan “jejak” atau posisi yang ditinggalkan oleh unsur kalimat yang bergeser ke depan. Pada kalimat tanya (4.b) dan (5.b), pergeseran apa dan siapa ke awal kalimat mengakibatkan dua hal: munculnya yang setelah kata tanya, dan perubahan verba dari bentuk aktif (meN-) ke bentuk semi-pasif (Kaswanti Purwo 1989: xiii).3
Transformasi ini dibahas oleh Cole et al. (2005) dengan menggunakan teori generatif mutakhir, Teori Minimalis. Mereka berpendapat bahwa transformasi ini mengubah kalimat verbal (4.a, 5.a) menjadi kalimat nominal (4.b, 5.b). Kalimat (4.b), misalnya, mereka analisis sebagai berikut:
- [Apa]FN [yang ia kirimkan j kemarin]FN
Ini adalah kalimat nominal, yang terdiri dari FN1 dan FN2. FN1 adalah predikat yang digeser ke depan, dan FN2 adalah klausa adjektiva tanpa pokok nomina (a noun head).
Menururt hemat saya, analisis ini terlalu teoritis. Bila kita menggunakan teori generatif klasik (Chomksy 1957 dan 1965), seperti yang digunakan Pak Samsuri, perubahan dari (4.a) menjadi (4.b) dapat dijelaskan dengan formula berikut:
- FN1 + meN-V + FN2 + Fadvà(b) – KT = kata tanya
- FN1 + meN-V + KT + Fadvà(c)
- KT + yang + FN1-V + j + Fadv
Ada dua langkah transformasi: (a)à(b)à(c). Pada langkah (b), FN2 paket itu berubah menjadi KT apa. Pada langkah (c), ada tiga peristiwa sintaktik: KT bergeser ke depan meninggalka jejak j, yang muncul setelah KT, dan verba aktif meN-V berubah menjadi FN1-V. Dengan formula ini, pergeseran KT ke awal kalimat serupa dengan wh-movement dalam bahasa Inggris, dan kalimat aktif berubah menjadi semi- pasif.
Tentu saja kasus transformasi seperti (4.a, 5.a) menjadi (4.b, 5.b) masih merupakan topik terbuka, yang layak untuk dikaji dan diperdebatkan lebih lanjut. Sintaksis bahasa Indonesia masih memerlukan penelitian intensif untuk menuju tata- bahasa baku tanpa menjadi beku.
Tata Kalimat yang telah diulas singkat ini adalah buku pertama dari “tiga serangkai” karya Pak Samsuri tentang “tata-bahasa Indonesia”. Buku kedua, Morfologi dan Pembentukan Kata, dinyatakan terbit tahun 1988 (badanbahasa.kemdikbud.go.id). Sayang, buku tata-kata ini tidak bisa ditemukan. Buku ketiga, tata-bunyi, juga direncanakan untuk ditulis (1985: ix, 42), tetapi tidak ada beritanya setelah itu. Maka, ulasan saya tentang sumbangan akademik Pak Samsuri terhadap upaya pembakuan bahasa Indonesia terbatas pada bidang sintaksis. Namun, seperti dinyatakan oleh Pak Anton Moeliono, Tata Kalimat telah membawa angin segar bagi sintaksis bahasa Indonesia, karena buku ini memaparkan struktur kalimat bahasa Indonesia sebagaimana digunakan oleh para penuturnya. Mendengarkan, mencermati, dan mengikuti “apa kata data” ternyata lebih mencerahkan daripada setia-dan-fanatik terhadap “apa kata teori”.
MERENGKUH LINGUISTIK-MAKRO DAN MENENGOK KEMBALI BAHASAJAWA
Seperti telah disebutkan di depan, ketiga karya terakhir Pak Samsuri adalah “Studi Wacana” (1990), “Kemampuan Pembicara BJ” (1993), dan “Pengaruh BI pada BJ” (1994). (Sekedar mengingatkan pembaca, BI kependekan dari bahasa Indonesia, dan BJ kependekan dari bahasa Jawa.) Ketiga karya tahun 1990-an ini menunjukkan bahwa Pak Samsuri juga memberikan perhatian serius terhadap studi bahasa dalam-konteks, baik konteks wacana maupun konteks sosio-kultural. Pada bagian berikut, “Studi Wacana” diulas sebagai upaya merengkuh linguistik-makro, sedangkan “Kemampuan Pembicara BJ” dan “Pengaruh BI pada BJ” disarikan sebagai upaya menguak kembali struktur internal dan fungsi sosial bahasa Jawa.
Dari Linguistik-mikro ke Linguistik-makro
Aliran Linguistik menyarikan dan menyajikan sembilan teori besar. Namun, semua teori bahasa ini berada dalam wilayah linguistik-mikro, yang satuan analisisnya terbatas pada kalimat. Linguistik-mikro adalah linguistik bebas- konteks, dan makna yang dibahas terbatas pada makna kata dan kalimat. Ini berbeda dengan linguistik-makro, atau linguistik dalam-konteks. Makna yang dibahas ditentukan oleh konteks. Implikasi dari studi bahasa dalam-konteks ialah penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Menurut Lavandera (1988), linguistik- makro meliputi empat sub-disiplin: pragmatik (dengan konteks antar-penutur), analisis wacana (dengan konteks tekstual), sosiolinguistik (dengan konteks sosial), dan etnolinguistik (dengan konteks kultural). Terkadang terjadi tumpang-tindih antara sosiolinguistik dan etnolinguistik, sehingga muncullah konteks sosio–kultural.
Meskipun Aliran Linguistik tidak membahas teori-makro, benih-benih linguistik–makro telah nampak dalam Tata Bahasa. Salah satu kekurangan teori generatif, dan sekaligus juga kelebihannya, ialah sikap-abai terhadap konteks, dan dengan demikian juga terhadap bahasa sebagai alat komunikasi. Melihat kekurangan ini, Pak Samsuri menyatakan, “kami ingin memasukkan aspek komunikasi dalam peristiwa bahasa” (1985: 40-41). Dalam bahasa lisan, komunikasi terjadi antar penutup dalam bahasa tulis, komunikasi terjadi antara penulis dan pembaca. Dalam sebuah percakapan yang melibatkan dua mitra tutur, peristiwa bahasa dapat ditampilkan pada Diagram 1.
Diagram 1. Negosiasi Makna dalam Percakapan
Diagram 1 ini saya sarikan dari penjelasan Pak Samsuri (1985: 41) tentang negosiasi makna yang terjadi antar-penutur. Makna dalam pikiran penutur A disampaikan melalui ungkapan, atau tuturan, yang kemudian didengar dan dipahami oleh penutur B, sehingga makna yang sama tertangkap oleh pikiran penutur B. Demikian pula ketika penutur B menanggapi apa yang telah diucapkan oleh penutur A, ia pun menyampaikan makna lewat ungkapan yang dipahami dan diterima oleh penutur A. Proses negosiasi makna dalam sebuah percakapan menyerupai snow–balling, salju yang menggelinding dan membesar. Setiap tuturan menciptakan konteks baru untuk tuturan berikutnya. Keseluruhan wacana yang dihasilkan oleh sebuah percakapan memiliki kepaduan (coherence), yang diciptakan bersama oleh dua penutur. Sedangkan untuk wacana yang dihasilkan oleh monolog atau karangan- tunggal, kepaduan diciptakan oleh seorang penutur atau penulis (Thornsbury 2005: 35-83).
“Referensi dan Inferensi di dalam Wacana”, karya Pak Samsuri yang terbit di jurnal Linguistik Indonesia (1990), berada dalam dua sub–disiplin sekaligus: analisis wacana dan pragmatik. “Studi Wacana” ini mengkaji bagaimana makna tersampaikan dari penutur kepada petutur, atau dari penulis kepada pembaca. Di antara aspek-aspek penting wacana dan kewacanaan adalah konteks, konteks, kohesi, koherensi, keterbacaan, implikatur, dan pra-anggapan (1990: 55). Dua yang terakhir ini dekat dengan referensi dan inferensi, rujukan-tersurat dan rujukan-tersirat. Dari “Studi Wacana” ini, tiga topik-kecil saja yang dikupas: (i) berkurang tanpa salah- paham, (ii) metafora lokal-kontekstual, dan (iii) menangkap yang tersirat dari yang tersurat. Contoh-contoh yang saya gunakan di sini tidak selalu persis dengan contoh dalam artikel.
Apakah yang dimaksud dengan berkurang tanpa salah paham? Makna yang diungkapkan penutur secara umum dipahami dengan benar oleh pendengar, meskipun aspek rincinya tidak tersampaikan.
- Biasanya ayah membaca koran di beranda (1990: 57)
Bila saya mendengar tuturan ini dari seorang kawan, yang ayahnya tidak saya kenal dan rumahnya tidak saya ketahui, maka makna yang saya tangkap adalah orang tua laki-laki kawan saya itu kebiasaannya membaca surat kabar di teras-depan rumahnya. Pemahaman saya ini benar. Sementara itu, informasi yang dimiliki kawan saya jauh lebih banyak dan lebih rinci. Dalam kalimat (8), “biasanya” merujuk pada waktu pagi, antara jam 7 dan 8, “ayah” merujuk pada laki-laki tua, berusia 70 tahun, berambut putih, kegemarannya memakai sarung dan kaos oblong putih, “membaca” merujuk pada kegiatan mencermati artikel-artikel tentang politik, budaya, olah raga, dan kesehatan, “koran” merujuk pada Kompas, dan “di beranda” merujuk pada kursi rotan di teras depan rumah yang penuh dengan tanaman hias.
Bagi penutur, kalimat (8) adalah intisari dari berpuluh-puluh informasi rinci yang melingkupi setiap kata utama (content word) di dalamnya. Bagi pendengar, kalimat itu sekedar informasi umum yang bersifat global. Tentu saja “global” dan “rinci” ini juga tergantung pada pengalaman dan pengetahuan pendengar. Bagi orang yang sering bepergian naik pesawat terbang, ketika mitra tutur mengucapkan “bandara Cengkareng”, ia bukan hanya menangkapnya secara global, melainkan juga mampu membayangkan luasnya bandar udara itu, megahnya bangunan-bangunan di sana, bagaimana antre mendapatkan boarding pass, dan seterusnya. Singkatnya, makna sejati dari sebuah tuturan atau kalimat sering merupakan inti dari jaringan informasi yang sangat luas.
Selanjutnya, bahasa sehari-hari tidak lepas dari metafora atau perlambang. Ketika seseorang mengumpat, Dasar kambing!, kejengkelannya yang memuncak telah membinatangkan orang yang diumpat bodoh dan tidak tahu aturan. Sebaliknya, penggunaan metafora bisa juga berisi pujian.
- Karim itu Chairilnya jurusan kita (1990: 59)
Panggunaan “Chairilnya” dalam kalimat (9) menyatakan bahwa Karim sangat berbakat menulis puisi. Ini adalah metafora lokal-kontekstual. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 1945, yang sebagian sajaknya, seperti “Aku” dan “Krawang Bekasi”, hampir selalu diajarkan kepada siswa SLTP di seluruh Indonesia. Jadi makna “Chairilnya” dalam tuturan (9) bisa langsung dipahami berkat pengetahuan dasar pendengar tentang sastra Indonesia. Karena itu, untaian dua kalimat (10) membingungkan.
- Karim itu Chairilnya jurusan kita. Lukisannya sering dipajang di sini.
Kalimat pertama bisa dimengerti, tetapi tidak ada hubungan yang relevan dengan kalimat kedua. Bagaimana mungkin seorang penyair memamerkan lukisan? Kalimat (11) mungkin juga tidak jelas maknanya, tetapi dengan alasan yang berbeda.
- Karim itu Whitman-nya jurusan kita
Siapa itu Whitman? Jika pendengar adalah mahasiswa Amerika yang sudah lancar berbahasa Indonesia, maka ia akan langsung mengerti. Walt Whitman (1819-1892) adalah penyair Amerika terkenal, penulis Leaves of Grass, yang hidup pada abad kesembilan belas. Bagi orang Indonesia, metafora ini bukan lokal dan tidak kontekstual, sehingga maknanya tidak jelas.
Terakhir, kehalusan budi manusia sering terungkap lewat makna tersirat, terutama jika penutur berupaya untuk tidak menyinggung perasaan pendengar (1990: 61). Saya punya contoh favorit. Bayangkan seorang dosen sedang mengajar, sementara di koridor para mahasiswa gaduh luar biasa, dan kemudian terjadi dialog berikut:
- A: Maaf, Dik, saya sedang mengajar.
B: Oh, tidak usah minta maaf, Pak. Silakan terus mengajar.
Secara harfiah, makna kedua tuturan ini saling terkait. Tetapi, jawaban tersurat yang diberikan oleh B tidak gayut dengan makna tersirat yang dimaksudkan oleh A. Pada ujaran A ada bagian-bagian yang tersembunyi, ditandai cetak miring berikut. Jika semuanya diungkapkan, akan kita dapatkan tuturan panjang (13).
- Maaf, Dik, jangan gaduh. Tolong semuanya diam. Saya sedang mengajar. Karena kalian gaduh, saya dan mahasiswa saya di kelas tidak bisa konsentrasi.
Tentu saja, dalam kenyataan, tidak ada mahasiswa yang menjawab dengan ujaran penutur B (12). Semua penutur normal pasti memiliki kemampuan pragmatik, sehingga mampu menangkap makna tersirat dari penutur A(12).
Apa yang dapat kita simpulkan dari ketiga uraian singkat di atas? Setiap penutur bukan hanya memiliki kompetensi bahasa (Chomsky 1965), melainkan juga kompetensi komunikatif (Hymes 1972) serta “pengetahuan umum” yang diperlukan untuk berwacana dengan penutur lainnya. Ia bukan hanya mampu membedakan mana kalimat yang gramatikal dan tak-gramatikal, melainkan juga mampu menangkap maksud mitra tutur, baik yang tersurat maupun tersirat, dan juga makna yang terungkap lewat perlambang lokal kontekstual.
Rindu Kampung: Menguak Kembali Bahasa Jawa
Apa yang dimaksud dengan “rindu kampung”? Tesis master Pak Samsuri, karya-tama beliau yang pertama, adalah The Phonology of Javanese (1958). (Sayang, tesis ini tidak bisa ditemukan untuk diulas.) Karya-karya penting selanjutnya yang beredar luas di tanah air adalah tentang linguistik umum dan linguistik bahasa Indonesia. Setelah tiga-puluh lima tahun, nampaknya beliau rindu kampung dan menengok kembali linguistik bahasa Jawa. “Kemampuan Pembicara BJ” (1993) mencermati struktur internal bahasa Jawa sebagai kompetensi bahasa penuturnya, dan “Pengaruh BI pada BJ” (1994) mengamati perubahan bahasa Jawa, baik pada struktur internalnya maupun fungsi sosialnya sebagai sarana komunikasi pada era kehidupan modern.
Perbedaan Bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nampak mencolok pada adanya tingkat tutur: ngoko, madya, dan krama, atau ‘rendah, sedang, dan tinggi’ (Poedjosoedarmo et al. 1979). Namun, untuk menyederhanakan pemaparan, Pak Samsuri menyetujui pendapat Pak Sudaryanto (1991) dan membagi tingkat tutur menjadi dua macam saja: ngoko dan krama. Dari berpuluh-puluh ribu kosakata bahasa Jawa, jumlah kata yang memiliki bentuk ngoko dan krama tidak lebih dari seribu. Tetapi kontras antara ngoko dan krama selalu muncul sangat jelas karena semua kata sarana (pronomina, preposisi, kata-sambung, kata-penunjuk, kata-tanya) dan sebagian besar afiks berfrekuensi tinggi selalu memiliki bentuk ngoko (N) dan krama (K), seperti nampak pada contoh (14) dan (15).
- Ini buku siapa?
- N: Iki buku-ne sapa?
- K: Menika buku-nipun sinten?
Kalimat bahasa Indonesia (14) memiliki padanan (15.a) dan (15.b) dalam bahasa Jawa, N dan K. Nomina buku memiliki bentuk N dan K yang sama, tetapi dua kata sarana dan afiks yang menyertainya dalam (15.a) dan (15.b) memiliki bentuk N dan K yang berbeda: iki : menika, -ne : -nipun, sapa : sinten. Maka tuturan K selalu berbeda secara mencolok dari tuturan N, sehingga keduanya dapat dipandang sebagai kode yang berbeda. Dalam sebuah percakapan, dimana penutur bahasa Jawa beralih dari bentuk N ke K atau sebaliknya, peristiwa tutur ini dapat dianggap sebagai alih kode (Poedjosoedarmo et al. 1979: 37-43). Dengan kata lain, bentuk N dan K mirip dengan “dua bahasa” yang berbeda.
Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, yang tak memiliki tingkat tutur berjenjang, pengucapan dan pemahaman ujaran cukup melibatkan tiga komponen bahasa: semantik, sintaksis, dan fonologi. Tetapi untuk bahasa Jawa, harus ditambahkan komponen pragmatik (1993: 411-13). Mengapa? Dalam setiap komunikasi verbal, penutur bahasa Jawa selalu mempertimbangkan siapa mitra tuturnya—dari segi usia, status sosial, dan tingkat keakraban. Masing-masing faktor ini dipecah lagi. Usia bisa lebih tua, sebaya, atau lebih muda. Status sosial bisa lebih tinggi, sederajat, atau lebih rendah. Tingkat keakraban bisa tak kenal, sekedar kenal, dan akrab. Persilangan antara sub-sub faktor inilah yang kemudian menentukan pemilihan tingkat tutur: N atau K. Misalnya, untuk kalimat bahasa Indonesia (16.a), jika ditujukan kepada adik, digunakan tuturan (16.b), tetapi jika ditujukan kepada ayah, digunakan tuturan (16.c).
- Harganya berapa?
- N: Regane pira?
- K: Reginipun pinten?
Jadi, istilah “pragmatik” digunakan oleh Pak Samsuri tidak dalam pengertiannya yang umum. Karena penutur bahasa apa pun, dalam setiap percakapan, selalu menggunakan kompetensi pragmatik-nya untuk menghasilkan tuturan yang santun. Menurut hemat saya, beliau menggunakan istilah ini dalam pengertian yang lebih khusus: “sosio-pragmatik” dan “etno-pragmatik”. Yang pertama merujuk pada faktor-faktor sosial seperti yang dikemukakan oleh sosiolinguistik, yang kedua merujuk pada faktor sosio-kultural, terutama pada kesantunan khas Jawa, yang dikaji oleh etnolinguistik. Ini nampak pada “Telaah Pustaka” (1993: 406-08). Di sini muncul nama antropolog Malinowski (1956), yang menyatakan bahwa tuturan dan situasi-tutur saling terkait erat, sehingga makna tuturan selalu ditentukan oleh situasi-tutur, dan juga nama ahli semiotika Umberto Eco (1976), yang menyatakan bahwa bahasa sebagai sistem tanda pada hakikatnya merupakan sistem tata-nilai dan tingkah-laku.
Hal baru yang dikemukakan oleh Pak Samsuri adalah “wacana objektif” dan “wacana subjektif” (1993: 407-08, 1994: 183-86). Wacana objektif adalah wacana yang tidak melibatkan mitra tutur dan/atau orang ketiga yang dihormati, wacana ini merujuk pada “sesuatu di luar sana” yang menjadi topik pembicaraan. Wacana ini memunculkan bentuk N jika ketakziman terhadap mitra tutur tidak diperlukan, dan bentuk K jika ketakziman diperlukan. Kalimat bahasa Indonesia (17) memiliki padanan (18.a) dan (18.b) dalam bahasa Jawa (1994: 183).
- Gunung Semeru di Jawa Timur itu tinggi sekali.
- N: Gunung Semeru ing Jawa Wetan iku dhuwur banget.
- K: Gunung Semeru ing Jawi Wetan menika inggil sanget.
Sebaliknya, wacana subjektif melibatkan mitra tutur dan/atau orang ketiga yang dihormati. Dengan mempertimbangkan tingkat keakraban dan ketakziman terhadap mitra tutur, selain bentuk N dan K, muncul pula bentuk ngoko alus (NA) dan krama alus (KA), kata alus berarti halus. Kalimat bahasa Indonesia (19) memiliki empat padanan dalam bahasa Jawa: N, K, NA, dan KA(1994: 184).
- Kamu kemarin pergi ke mana?
- N: Kowe dhek wingi lunga menyang endi?
- K: Sampeyan kala wingi kesah dhateng pundi?
- NA: Panjenengan dhek wingi tindak menyang endi?
- KA: Panjenengan kala wingi tindak dhateng pundi?
Tabel 3. Perubahan Kata/Frasa dari N ke K, NA, dan KA
| Bahasa Indonesia | Ngoko | Krama | Ngoko Alus | Krama Alus |
| Kamu | Kowe | sampeyan | panjenengan | panjenengan |
| kemarin | dhek wingi | kala wingi | dhek wingi | kala wingi |
| Pergi | Lunga | kesah | tindak | Tindak |
| ke mana | menyang endi | dhateng pundi | menyang endi | dhateng pundi |
Untuk memudahkan penjelasan, perubahan kata dari bentuk N menjadi K, NA, dan KA dicantumkan pada Tabel 3. Dari N ke K, perubahan koweàsampeyan dan lungaàkesah menyarankan ‘ketakziman sedang’. (Lambang anak panah [à] berarti ‘menjadi’.) Sedangkan dari N ke NA/KA, perubahan koweàpanjenengan dan lungaàtindak menyarankan ‘ketakziman tinggi’. Secara sintaktik, hubungan ketakziman antara pronomina kedua dan verba pada (20.b, c, d) adalah hubungan predikatif. (Hubungan lain [tanpa contoh di sini] adalah hubungan atributif dan posesif.) Perhatikan pula bahwa pada perubahan dari N ke K dan KA, semua kata berubah, sedangkan dari N ke NA, hanya pronimina kedua dan verba-predikatif yang berubah, adverbia dhek wingi ‘kemarin’ dan menyang endi ‘ke mana’ tidak berubah. Penggunaan NAmenyarankan ‘ketakziman tinggi’ dan ‘keakraban’.
Dari pembahasan singkat tentang empat tingkat tutur bahasa Jawa ini, apa yang dapat kita simpulkan? Ada tiga hal. Pertama, keempat tingkat tutur tersebut tidak berbeda secara sintaktik, tetapi hanya berbeda secara leksikal. Perbedaan leksikal itu menyarankan adanya tiga tingkat ketakziman: 0 “nol”, sedang, dan tinggi. Kedua, dalam tindak-tutur yang ditentukan oleh wacana objetif atau subjektif, kata- kata dengan tingkat ketakziman yang berbeda itu dipilih dari poros paradigmatik dan diproyeksikan pada poros sintagmatik, sehingga menghasilkan tingkat tutur tertentu. Ketiga, kesantunan Jawa telah menghasilkan sistem leksikal yang kompleks pada poros paradigmatik, dan sistem proyeksi yang kompleks pula pada poros sintagmatik. Akibatnya, pemerolehan bahasa Jawa sebagai bahasa pertama merupakan proses psikologis yang sangat rumit. Walhasil, tidak mengherankan jika generasi penutur bahasa Jawa hari ini pada umumnya tidak fasih menggunakan bahasa ibu mereka. Inilah yang ditelaah dengan cermat pada bagian akhir “Pengaruh BI pada BJ” (1994: 189-91).
Pada awalnya, seperti telah disinggung di depan, upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi kehidupan modern telah mengakibatkan terjadinya ledakan jumlah kosakata yang begitu besar. Ketika bahasa Jawa digunakan dalam konteks yang sama, kosakata baru bahasa Indonesia itu pun kemudian diserap secara masif oleh bahasa Jawa. Mari kita simak kutipan dari Panyebar Semangat (23 Mei 2009: 38) berikut (cetak miring ditambahkan), beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- Penyakit kronis iku bisa awujud artritis, radang usus besar, kolesterol, anemia, hipertensi lan hipotensi, stres, obesitas, lan sapanunggalane.
- Penyakit kronis itu bisa berupa artritis, radang usus besar, kolesterol, anemia, hipertensi dan hipotensi, stres, obesitas, dan lain sebagainya.
Kalimat (21) yang dikutip dari majalah mingguan berbahasa Jawa itu terdiri dari 18 kata, dan 12 di antaranya adalah kata pinjaman dari bahasa Indonesia, yang hampir semuanya (kecuali penyakit dan radang usung besar) diserap dari bahasa asing (Inggris). Bagi penutur non-Jawa pun, makna kalimat (21) langsung bisa ditebak dan kemungkinan besar dapat dimengerti. Secara fonologis, iku dekat dengan itu, bisa awujud dekat dengan bisa berwujud, lan dekat dengan dan, lan sapanunggalane bisa ditebak dari konteks, dan sebagainya.
Pengaruh ledakan leksikal dan serapan tamak itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting dan diulas secara tajam adalah penyusutan yang drastis dari penggunaan tingkat tutur krama. Subjek penelitian yang digunakan oleh Pak Samsuri adalah 60 keluarga Jawa di kota Surabaya dan Malang. Suami-isteri dari semua keluarga itu, rata-rata berusia sekitar 60 tahun, adalah penutur bahasa Jawa yang fasih menggunakan keempat tingkat tutur: N, K, NA, dan KA. Pada waktu putera-puteri mereka masih kecil, mereka dibesarkan dan dididik menggunakan keempat jenis tingkat tutur tersebut. Namun, setelah anak-anak itu dewasa, bekerja, dan berkeluarga–sebagian besar tinggal jauh dari Surabaya atau Malang, mereka tidak lagi menggunakan bahasa Jawa krama. Dengan kedua orang tua, mereka menggunakan NA, dan bahkan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia.
Apa komentar Pak Samsuri? Beliau mengambil sikap sebagai pengamat yang objektif. Tidak ada penyesalan atau keluh-kesah terhadap menyusutnya penggunaan bahasa Jawa krama. Bahkan beliau merujuk pada “Gerakan Jawa Dwipa” (di bawah arahan R. Tjokrosoedarmo di Surabaya pada tahun 1920-an), yang menganjurkan agar tingkat-tutur bahasa Jawa yang berjenjang itu dihapus, dan cukup digunakan satu tingkat tutur saja, yaitu ngoko (1994: 189-91). Nampaknya, dengan pesatnya kemajuan zaman dan datangnya kehidupan modern, cita-cita dari gerakan demokratisasi bahasa Jawa itu akhirnya tercapai juga. Hanya tingkat tutur N dan NA yang digunakan oleh mayoritas penutur bahasa Jawa, dan ini digunakan berdampingan erat dengan bahasa Indonesia. Tentu saja, setelah dua-puluh tahun berlalu, hasil penelitian ini perlu dikaji ulang: seperti apa penggunaan bahasa Jawa di Surabaya dan Malang saat ini?
Dari “Studi Wacana” dan “Penelitian Bahasa Jawa” tersebut, kita tahu bahwa sampai di ujung karier ilmiahnya, Pak Samsuri tetap seorang bahasawan kontemporer dan berpikiran terbuka. Beliau tekun mengikuti perkembangan linguistik mutakhir dan cermat mengamati kehidupan bahasa Jawa di bawah bayang- bayang bahasa Indonesia. Selama lebih dari empat-puluh tahun beliau menekuni fonetik, fonologi, morfologi, dan sintaksis cabang-cabang penting dari linguistik- mikro. Namun, ketika sejak tahun 1970-an studi bahasa semakin meluas dan mencakup berbagai jenis konteks, beliau pun tidak segan keluar sejenak dari linguistik-mikro dan melongok ke serambi linguistik-makro. Kerinduan beliau “pulang kampung” dengan menguak kembali kehidupan bahasa Jawa bukan kerinduan untuk bernostalgia, melainkan untuk mengambil potret bahasa Jawa hari itu—seperti apa adanya. Dari awal hingga akhir, beliau percaya bahwa bahasa adalah alat komunikasi, dan beliau percaya pada adanya wacana transaksional (1990: 55). Dengan kepercayaan itu, beliau telah menyampaikan seluruh pengetahuan linguistiknya kepada kita dengan bahasa yang jernih dan semangat ilmiah yang mencerahkan. Mengutip Tempo, semua karya beliau “enak dibaca dan perlu”. Karena suka humor, seandainya masih ada di antara kita, beliau akan menjawab, “Seperti tempe, enak dibacem dan perlu.”
SISI LAIN KEHIDUPAN PAK SAMSURI
Dari Pak Anton Moeliono, Pak Samsuri mendapatkan gelar kehormatan “pendekar bahasa”. Tetapi, seperti terbaca pada judul resensi ini, saya lebih suka menyebut beliau “begawan linguistik”. Dalam bahasa-gaul, “pendekar” adalah akronim untuk pendek dan kekar. Dalam pewayangan, pendekar lebih mengacu pada tokoh perkasa seperti Bima atau anaknya, Gatutkaca. Gambaran tentang Pak Samsuri agak jauh dari itu. Beliau lebih mirip dengan Abiyasa, begawan di Wukir Retawu. IKIP Malang, kini UM, juga mirip dengan padepokan sang begawan itu, karena dikelilingi enam gunung: Semeru, Bromo, Welirang, Arjuna, Kawi, dan Kelud. Ini bukan argumentasi tentang gelar mana yang lebih cocok, tetapi sekedar menjelaskan selera pilihan pribadi.
Julukan “pendekar” maupun “begawan” sama-sama menyarankan kehebatan beliau. Pak Samsuri unggul bukan hanya sebagai ilmuwan, melainkan juga sebagai pemimpin. Ketika beliau menjabat Dekan FKSS (1965-1970) dan Rektor IKIP Malang (1970-1974), saya belum menjadi mahasiswa di kampus ini. Namun kedua jabatan penting itu jelas menunjukkan bahwa beliau juga handal sebagai administrator dan pemimpin perguruan tinggi. Kepeloporan beliau juga menonjol dalam membina ilmu bahasa. Beliau adalah salah satu pendiri Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI), yang langsung terpilih sebagai ketuanya yang pertama, dan tugas itu diembannya selama enam tahun (1975-1981). Selain itu, beliau juga pernah menjadi anggota Steering Committee bagi Regional English Language Center (RELC), SEAMEO di Singapura (1967-1972), sebagai wakil (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) Indonesia. Artinya, kepemimpinan dan keahlian beliau juga diakui di kawasan Asia Tenggara.
Saya merasa beruntung pernah diajar oleh Pak Samsuri. Humor yang dikutip di awal tulisan ini saya catat sewaktu beliau mengajar Cross-cultural Understanding pada tahun 1981. Di kelas itu, ada kawan mahasiswa yang menulis makalah dengan judul “My Alternation in Using Indonesian and English”. Kata beliau, “kalau judulnya my alternation …, Anda kan nlungsungi” (berganti kulit seperti ular). Humor lain yang saya ingat ialah sewaktu mengikuti Penataran Prajabatan tahun 1984. Ketika beliau telah masuk ruang dan siap memberikan ceramah, semua petatar berdiri tegak dengan sikap sempurna dan Ketua Kelompok berbicara tegas dan keras, “Kami peserta Prajabatan siap mengikuti penataran hari ini. Laporan selesai”. Dengan santai beliau menjawab, “Terus la apa?” (Terus ngapain?). Semua peserta pun tertawa terpingkal-pingkal. Jawaban itu mengisyaratkan bahwa beliau tidak menyukai disiplin militeristik dibawa ke dalam dunia akademik. Kemudian, di awal ceramah tentang GBHN, beliau mengutip, “Garis-garis Besar Haluan Negara adalah Haluan Negara dalam Garis-garis Besar …, lalu berkomentar, Padha ae karo ora omong apa-apa” (Sama saja dengan tidak bicara apa-apa). Ini kritik beliau terhadap verbalisme—omong besar dan penggunaan bahasa yang boros dan sia-sia.
Menjelang tamat Program S1, sewaktu melewati Gedung H1, beberapa kali saya melihat Pak Samsuri datang untuk mengajar di Fakultas Pascasarjana (sekarang Program Pascasarjana) naik sepeda jengki warna biru metalik. Sepeda itu disandarkan pada dinding gedung di sebelah timur H1. Alangkah sederhananya Profesor Samsuri, Ph.D., sang pakar linguistik yang mantan Dekan dan mantan Rektor. Tidak ada post-power syndrome, juga tidak berpura-pura bersahaja. Itulah beliau, yang menjalani kehidupan asketik, tak silau pada kemewahan duniawi, dan tampil apa adanya. Semua yang terbaik telah beliau berikan kepada IKIP Malang, kepada kita semua murid-muridnya, dan kepada semua pencinta bahasa dan ilmu bahasa di tanah air. Kita semua yakin bahwa saat ini “di sana” beliau juga tidak mengidap post-worldly life syndrome. Semua yang harus ditunaikan telah beliau kerjakan sebaik-baiknya.
The day is done and the darkness
Falls from the wings of the Night
As a feather is wafted downward From
an eagle in his flight
Hari telah usai dan kegelapan
Jatuh dari sayap Gelap-malam
Seperti sehelai bulu jatuh melayang
Dari sang garuda yang jauh terbang4
Sang garuda, sang begawan linguistik, telah terbang jauh meninggalkan kita. Di sini terhampar senyap dan harap. Di luar hari telah gelap, Pak Sam, guruku. Hari telah malam, “Selamat malam”.
Catatan
1 Keempat karya Pak Samsuri yang tidak dapat saya temukan tercatat pada dua sumber: (1) “Sedikit tentang Pengarang Buku Ini” pada halaman terakhir (507) Tata Kalimat Bahasa Indonesia (1985), dan (2) Samsuri dalam rubrik “Tokoh” pada laman badanbahasa. kemdikbud.go.id.
2Terhadap Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), yang memprakarsai upaya pengembangan dan pembakuan bahasa Indonesia pada zaman Orde Baru, ada dua kritik, dari pakar studi budaya (cultural studies) Ariel Heryanto dan sastrawan Alif Danya Munsyi. Melalui laporan penelitiannya, Language of Development and Development of Language: the Case of Indonesia, yang diterbitkan sebagai manuskrip Pacifics Linguistics seri-86, Ariel Heryanto (1995: 38-52) menyoroti kinerja P3B secara kritis—dalam konstelasi politik Orde Baru. Bahasa Indonesia berkembang sangat pesat, terutama lewat penambahan kosakata dan istilah baru, yang jumlahnya ribuan atau bahkan puluhan ribu. Namun, pada saat itu ada dua kekuatan besar yang berhadap-hadapan: pemerintah otoriter vs. rakyat yang menginginkan kebebasan berpendapat, dan politisi-birokrat vs. ilmuwan- bahasawan. Pada antagonisme pertama, pemerintah ingin mengontrol pikiran masyarakat dengan bahasa-kekuasaan. Pada antagonsime kedua, politisi-birokrat memiliki dan menyukai bahasa-kekuasaan mereka sendiri, sedangkan bahasawan- ilmuwan berupaya keras mengembangkan bahasa Indonesia menjadi sarana-utuh yang mampu sepenuhnya mengungkapkan gagasan keilmuan dan teknologi modern yang super-kompleks.
Manuskrip Ariel Heryanto terbit tahun 1995, di akhir era Orde Baru. Pada zaman reformasi, P3B berubah nama menjadi Pusat Bahasa (tahun 2000), dan kemudian berganti lagi menjadi Badan Bahasa (tahun 2010). Perubahan nama ini mestinya juga menunjukkan adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan bahasa Indonesia selanjutnya. Dengan demikian, tesis Ariel Heryanto tersebut perlu dikaji ulang, dengan mengajukan pertanyaan: pola pengembangan bahasa Indonesia model Orde Baru tersebut berlaku sampai kapan? Kemudian, adakah perubahan yang signifikan? Apa hasilnya? Bagaimana pula rencana dan proyeksi ke depan?
Kritik Alif Danya Munsyi, nama samaran Remy Sylado, disampaikan melalui tulisannya “Bahasa Kita Bukan Hanya Diurus Sarjana Bahasa” (1996 [2005]). Kritik ini lebih pedas daripada kritik Ariel Heryanto. Munsyi mencemooh P3B sebagai “Pusat Pembinasaan dan Pembingungan Bahasa” dan mengejek bahasa yang “baku cenderung kaku lalu tak laku” (hlm. 4). Bagi seorang “munsyi”, atau sastrawan- bahasawan, bahasa yang “indah dan tepat” lebih menarik daripada bahasa yang “baik dan benar”. Panduan terakhir ini berarti ‘santun dalam penggunaan’ (sesuai dengan kaidah pragmatik dan sosiolinguistik), dan ‘benar menurut aturan tata-bahasa’ (terutama aturan ejaan dan kaidah morfo-sintaktik). Ini urusan “sarjana bahasa”, kata Munsyi. Sementara pada panduan pertama, “indah” berarti mengikuti dorongan-dorongan estetik, dan “tepat” berarti mewujudkan penalaran yang jernih sambil menggali seluruh potensi kreativitas berbahasa. Selanjutnya ia memberikan ulasan, komentar, dan krtik terhadap ejaan bahasa Indonesia yang digunakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi pertama, cetakan ketiga (1990). Menurut pendapat saya, kritik pedas tersebut merupakan ungkap-verbal khas seorang sastrawan, yang telah menggelembungkan licentia poetica menjadi licentia linguistica. Kritik ini layak didengar, dan aspek yang konstruktif layak menjadi landasan kebijakan pengembangan bahasa Indonesia, kini dan di masa mendatang.
3 Istilah “semi-pasif” saya gunakan untuk memudahkan pemahaman. Istilah asli yang digunakan Profesor Bambang Kaswanti Purwo (1989: xiii) adalah “pasif tak- naratif”. Dalam buku Serpih-serpih Telaah Pasif Bahasa Indonesia yang beliau sunting banyak istilah lain untuk “semi-pasif” (tidak dipaparkan di sini) yang dikemukakan oleh para peneliti konstruksi pasif dalam bahasa Indonesia.
4 Puisi penutup tulisan ini adalah bait pertama dari “The Day is Done”, sajak karya Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882), yang dimuat dalam antologi 101 Great American Poems (hlm. 8-10), suntingan The American Poetry and Literary Project (1998), dan diterbitkan oleh Dover Publications, Inc. Terjemahan bait tersebut ke dalam bahasa Indonesia oleh saya sendiri, penulis resensi ini.
Ucapan Terima Kasih
Saya sangat berterima kasih kepada tiga insan budiman. Pertama, Ibu Katharina Endriati Sukamto, Ph.D., Ketua Masyarakat Linguistik Indonesia, telah membantu memberikan informasi lengkap tentang Profesor Anton M. Moeliono dan karya ilmiah terakhir Profesor Samsuri. Kedua, Pak Wahyu Widodo, M. Hum., bahasawan muda jenis-langka dan kolega di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang, telah bermurah hati meminjamkan karya-karya penting Profesor Samsuri, mencarikan informasi tentang jejak-ilmiah beliau plus berbagai rujukan mutakhir, dan membaca-cermat draf awal resensi ini serta memberikan saran-saran perbaikan yang sangat berharga. Tanpa rujukan mutakhir yang melimpah dari Pak Wahyu, daftar pustaka tulisan ini akan nampak ketinggalan zaman. Bahkan ketika draf awal resensi ini telah tandas-tuntas, Pak Wahyu masih menemukan dua karya terakhir Profesor Samsuri. Maka clean draf itu saya bongkar, dan dua karya tersebut saya rangkum dan saya sisipkan. Ketiga, Bapak Drs. Bambang Tribagjo Prawirayuwono, M.Psi., Dip. UCLES, guru bahasa Inggris senior SMAN 1 Malang dan pakar-atque– pemelihara budaya Jawa, telah menjadi narasumber penting untuk ungkapan- ungkapan bahasa pedalangan dan Jawa Kuno serta nama sejumlah tokoh dunia wayang. Bantuan yang tulus dan tiada putus dari ketiga insan budiman tersebut sangat membantu saya dalam proses penulisan “resensi” ini. Segala kekurangan dalam tulisan ini adalah tanggung jawab saya pribadi.
Daftar Pustaka
Badudu, J. S. 1984. Pelik-pelik Bahasa Indonesia. Bandung: Pustaka Prima. Chomsky, Noam. 1957. Syntactic Structures. The Hague: Mouton.
Chomsky, Noam. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
Cole, Peter, Gabriella Hermon, dan Yassir Nasanius Tjung. 2005. How Irregular is WH in situ in Indonesian? Dalam Studies in Language 29-3: 553-581. New York: John Benjamins Publishing Company.
Collins, James T. 1998 [2011]. Bahasa Melayu Bahasa Dunia: Sejarah Singkat. (Terjemahan dari Malay, World Language: A Short History.) Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
Comrie, Bernard. 1989. Language Universals and Linguistic Typology (second edition.) The University of Chicago Press.
Foulcher, Keith. 2000. Sumpah Pemuda: the Making and Meaning of a Symbol of Indonesian Nationhood. Asian Studies Review, Volume 24 Number 3 September 2000: 378-410.
Hammerly, Hector. 1982. Synthesis in Language Teaching: An Introduction to Languistics. Blaine, W.A., U.S.A.: Second Language Publication.
Harris, Randy Allen. 1995. The Linguistics Wars. New York/Oxford: Oxford University Press.
Hymes, Dell. 1972. On Communicative Competence. Dalam Prides, J. B. & Holmes, J.(eds.). Sociolinguistics (pp. 269-85). Harmondsworth: Pinguin.
Jakobson, Roman. 1959 [1992]. On Linguistic Aspects of Translation. In Schulte, Rainer & Biguenet, John (eds.). Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida. Chicago and London: The University of Chicago Press.
Jakobson, Roman. 1960 [1987]. Linguistics and Poetics. Dalam Pomorska, K. & Rudy, S. Roman Jakobson, Language in Literature, pp. 62-94. Cambridge, Mass., London, England: The Belknap Press of Harvard University Press.
Kaswanti Purwo, Bambang (ed.). 1989. Serpih-serpih Telaah Pasif Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Lavandera, Beatriz R. 1988. The Study of Language in its Sociocultural Context. Dalam Newmeyer, Frederick J. (ed.). Linguistics: The Cambridge Survey, vol. IV: Language: The Socio-cultural Context, pp. 1-13. Cambridge: Cambridge University Press.
Lyons, John. 1978. Chomsky. Fontana Modern Masters Series. London: Fontana- Collins.
Moeliono, Anton M. Kepergian Empat Pendekar Bahasa (Wartamerta). Dalam Prosiding Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) 2009.
Panjebar Semangat No. 21, 23 Mei 2009.
Poedjosoedarmo, Soepomo, Th. Kundjana, Gloria Soepomo, dan Alip Suharso. 1979. Tingkat Tutur Bahasa Jawa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Samuel, Jerome. 2005 [2008]. Kasus Ajaib Bahasa Indonesia? Pemodernan Kosakata dan Politik Peristilahan. (Terjemahan dari Modernisation lexical et politique terminologique: Le cas de l’Indonesien.) Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Samsuri. 1978. Analisis Bahasa: Memahami Bahasa Secara Ilmiah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Samsuri. 1985. Tata Kalimat Bahasa Indonesia. Jakarta: Sastra Hudaya.
Samsuri. 1988. Berbagai Aliran Linguistik Abad XX. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
Samsuri. 1990. Referensi dan Inferensi di dalam Wacana. Linguistik Indonesia, Tahun 8 No. 2, Desember 1990: 56-65.
Samsuri. 1993. Kemampuan Pembicara Bahasa Jawa: Suatu Studi Permulaan. Dalam Kridalaksana, Harimurti (ed.). Penyelidikan Bahasa dan Perkembangan Wawasannya. Jakarta: Masyarakat Linguistik Indonesia.
Samsuri. 1994. Pengaruh Bahasa Indonesia pada Pemakaian Unggah-ungguh Bahasa Jawa. Dalam Sihombing, Liberty P., Multamina R. M. T. Lauder,
- Pamela Kawira, dan Nitrasattri Handayani (ed.). Bahasawan Cendekia: Seuntai Karangan untuk Anton M. Moeliono. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia & Internusa.
Sampson, Geoffrey. 1980. Schools of Linguistics. Stanford: Stanford University Press.
Sapir, Edward. 1921. Language: An Introduction to the Study of Speech. San Diego, New York, London: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers.
Slametmuljana. 1957. Kaidah Bahasa Indonesia I. Jakarta: Penerbit Djambatan. Sudaryanto (ed.). 1991. Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa. Yogyakarta: Duta
Wacana University Press.
Thornbury, Scott. 2005. Beyond the Sentence: Introducing Discourse Analysis.
Oxford: Macmillan.
Whitman, Walt. 1892 [1958]. Leaves of Grass. New York: New American Library.